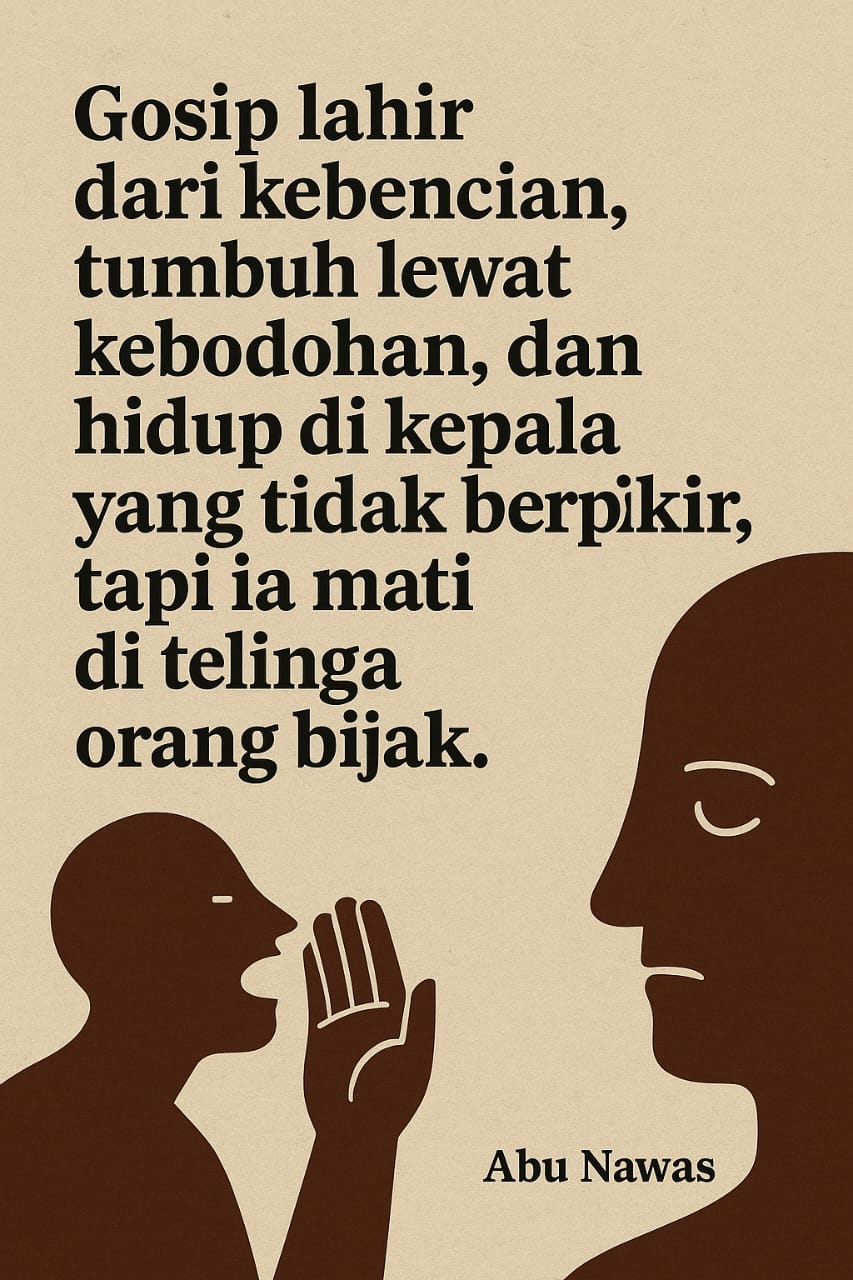Gosip: Racun yang Menyebar Lewat Lidah, Tapi Mati di Telinga Orang Bijak
Oleh: Fakhrurrazi, S.ST., M.Si
Penulis Reflektif Jiwa
OPINI - Dalam kehidupan sosial, gosip sering dianggap sebagai bumbu dalam pergaulan. Ringan, menyenangkan, bahkan menghibur. Tapi siapa sangka, di balik obrolan yang tampak remeh itu, tersembunyi potensi kerusakan yang luar biasa: merusak nama baik, menghancurkan hubungan, dan menebar kebencian.
Gosip bukanlah sekadar kabar angin, tetapi produk dari emosi negatif, khususnya kebencian. Ia tumbuh subur di lahan kebodohan, yaitu pada orang-orang yang malas berpikir, tidak memverifikasi, dan justru merasa bangga menyebarkannya.
Sebagaimana dikatakan oleh tokoh legendaris dunia Islam, Abu Nawas:
"Gosip lahir dari kebencian, tumbuh lewat kebodohan, dan hidup di kepala yang tidak berpikir. Tapi ia mati di telinga orang bijak."
Kalimat ini bukan sekadar sindiran, melainkan tamparan moral bagi kita semua yang hidup di era digital, di mana informasi bertebaran tanpa kendali. Hari ini, gosip tak lagi bergema dari mulut ke mulut, tetapi melesat lewat jari-jari dalam bentuk tangkapan layar, potongan video, status penuh insinuasi, bahkan pesan berantai yang menghakimi tanpa tabayun.
Cermin Kehidupan dari Kisah Abu Nawas dan Bulu-Bulu yang Terbang
Dalam salah satu kisahnya, Abu Nawas dimintai nasihat oleh seorang pemuda yang menyesal telah menyebarkan kabar buruk tentang orang lain. Abu Nawas hanya menjawab dengan sebuah perintah yang aneh:
"Ambillah bantal bulu, robeklah di pasar, dan biarkan bulunya beterbangan. Lalu, kumpulkan kembali semua bulu itu."
Tentu saja pemuda itu tak mampu melakukannya. Bulu-bulu telah menyebar ke mana-mana, terbawa angin. Abu Nawas pun berkata, “Begitulah gosip. Sekali terucap, ia tak bisa ditarik kembali.”
Kisah ini sangat relevan dengan keadaan kita hari ini. Satu unggahan media sosial bisa menjadi viral dalam hitungan menit. Tapi setelah reputasi orang rusak, siapa yang bertanggung jawab? Setelah hubungan hancur, siapa yang akan memperbaikinya?
Di tengah derasnya informasi, kita dituntut untuk menjadi pribadi yang cerdas secara moral , tidak cepat percaya, tidak mudah menyebar, dan berani berkata “cukup sampai di sini.” Kita perlu membiasakan diri bertanya sebelum bicara:
Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini pantas untuk disebarkan?
Sayangnya, banyak yang lebih senang menyebarkan daripada menyaring. Lebih bangga menjadi “yang pertama tahu” daripada “yang paling bijak bersikap”.
Padahal, sebagaimana penyakit menular, gosip pun bisa menjadi epidemi sosial yang menghancurkan struktur kepercayaan dan harmoni.
Tulisan ini bukan hanya ajakan untuk berhenti bergosip, tapi ajakan untuk menumbuhkan etika berpikir sebelum berbicara. Kita tak bisa membungkam semua lidah yang jahat, tapi kita bisa memilih menjadi telinga yang tak memberi ruang bagi kabar bohong untuk berkembang.
Karena pada akhirnya, masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mampu menjaga lisan dan menakar kabar. Mari bersama membangun budaya klarifikasi, bukan sensasi. Budaya konfirmasi, bukan fitnah.
Jadilah seperti Abu Nawas yang memilih diam bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa diam bisa menjadi pelindung bagi kehormatan orang lain, dan cermin kebijaksanaan bagi dirinya sendiri.
Gosip memang tidak membutuhkan kebenaran. Ia hanya butuh satu telinga yang mau mendengar, dan satu lidah yang ingin membicarakan. Maka, putuskan rantainya di kita.
“Diam terhadap gosip bukan kelemahan, tapi pilihan moral untuk tidak ikut dalam kerusakan.” – Bang Aji