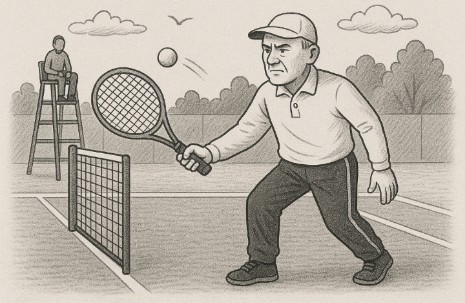Rebond Kekuasaan dan Bayang Dinasti Solo
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
OPINI - Samuel P. Huntington dalam Political Order in Changing Societies (1968) menulis bahwa negara dengan institusi lemah akan mudah dikooptasi oleh kekuatan informal. Ketika pranata politik gagal menyeimbangkan modernisasi dan stabilitas, maka yang muncul bukan tatanan, melainkan kekacauan yang terorganisir. Analisis itu kini menemukan relevansi di Indonesia pasca berakhirnya masa pemerintahan Joko Widodo.
Fenomena politik setelah lengsernya Jokowi memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak selalu berakhir bersama masa jabatan. Ia dapat hidup lebih lama dalam bentuk pengaruh, jaringan, dan loyalitas yang dibangun bertahun-tahun. Jokowi berhasil menanamkan loyalis di pelbagai sektor strategis, dari kabinet hingga lembaga hukum dan keamanan. Ia juga memelihara barisan relawan dan ormas yang pada dasarnya merupakan kekuatan politik informal dengan orientasi personalistik yang loyal kepada sosok, bukan sistem.
Bayang Kekuasaan Informal
Kecenderungan ini menciptakan apa yang oleh ilmuwan politik Guillermo O’Donnell disebut delegative democracy yaitu demokrasi yang secara prosedural tetap berjalan, tetapi dalam praktiknya direduksi menjadi otoritarianisme elektoral. Kekuasaan bergeser dari institusi kepada figur.
Ketika Joko Widodo berhasil menempatkan putranya sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, banyak pihak melihatnya sebagai simbol keberlanjutan pengaruh politik “Dinasti Solo.” Namun di balik itu, muncul pula kegelisahan, apakah pemerintahan hasil Pemilu 2024 benar-benar otonom, ataukah sekadar kelanjutan kekuasaan lama dalam wajah baru?
Dugaan bahwa ada “operasi garis dalam” yakni semacam infiltrasi politik dan psikologis untuk mengendalikan dinamika pemerintahan dari balik layar yang mengingatkan pada teori center of gravity dari Carl von Clausewitz. Dalam strategi militer, menghancurkan pusat gravitasi lawan berarti melumpuhkan sumber kekuatannya, yakni legitimasi dan kepercayaan publik. Maka ketika muncul serangkaian blunder kebijakan dan kontroversi di sekitar pemerintahan baru, mulai dari tanggung jawab proyek Kereta Cepat Whoosh, polemik tim reformasi Polri, hingga kegaduhan kasus hukum terkait ijazah Jokowi, sebagian kalangan menilai bahwa itu bukan sekadar kekeliruan administratif, tetapi bagian dari proses pelemahan legitimasi.
Narasi “Presiden Omon-omon”, yang beredar luas di media sosial, menjadi simbol perang psikologis. Dalam Psychological Warfare, Paul Linebarger menyebut propaganda paling efektif adalah yang menggorok luka batin rakyat — kemarahan terhadap janji yang tak ditepati, dan rasa frustasi terhadap ketimpangan sosial. Di tangan para pengendali opini, luka itu diubah menjadi alat mobilisasi massa.
Politik Bayangan dan Bahaya Institusional
Yang berbahaya dari operasi politik berbasis loyalitas personal adalah rusaknya prinsip impersonal power dalam demokrasi. Ketika kekuasaan dipersonifikasikan, dimana ketika negara bergantung pada figur, bukan sistem, maka negara mudah tersandera oleh jaringan tak terlihat berwajah ormas, relawan, atau elite ekonomi yang tumbuh dari rente kekuasaan.
Inilah inti kekhawatiran banyak ilmuwan politik, dimana negara yang gagal menegakkan otonomi institusinya akan tergelincir menjadi failed state bukan karena invasi luar, melainkan karena keropos dari dalam. Yugoslavia pada 1990-an menjadi contoh klasik, sebuah negara runtuh bukan karena kekalahan perang, tetapi oleh erosi kepercayaan, konflik elite, dan fragmentasi kekuasaan.
Jika dugaan tentang operasi politik di sekitar pemerintahan baru benar adanya, maka tantangan terbesar Presiden Prabowo bukan pada oposisi formal, tetapi pada kekuatan informal yang bekerja di jantung kekuasaan. Ia harus memilih, menjadi pemimpin yang berdiri di atas seluruh kekuatan politik, atau sekadar pelanjut dari sebuah dinasti yang belum usai.
Menjadi Negarawan, Bukan Bayangan
Dalam ilmu intelijen, setiap operasi selalu melahirkan kontra-operasi. Maka, bila benar ada “garis dalam”, negara harus merespons bukan dengan paranoia, tetapi dengan konsolidasi sistemik yang memperkuat lembaga hukum, mereformasi aparat keamanan, dan menata ulang arsitektur loyalitas dalam tubuh pemerintahan.
Presiden Prabowo harus membuktikan bahwa ia bukan “wayang” di tangan dalang lama. Untuk itu, ia perlu menegakkan garis batas yang tegas antara kekuasaan publik dan kekuasaan personal. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa, bukan balas jasa, bukan dendam politik, menjadi ukuran kenegarawanan sejati.
Jika ia gagal membaca dinamika ini, maka yang terjadi hanyalah pergantian pemain tanpa perubahan permainan, maka kekuasaan terus berputar dalam lingkaran setia kawan politik yang mengorbankan rakyat sebagai penonton abadi.
Dan ketika itu terjadi, maka yang disampaikan Huntington benar, bahwa institusi yang lemah bukan hanya gagal menegakkan tatanan, tetapi menjadi jalan bagi lahirnya kekacauan yang berwajah demokrasi.